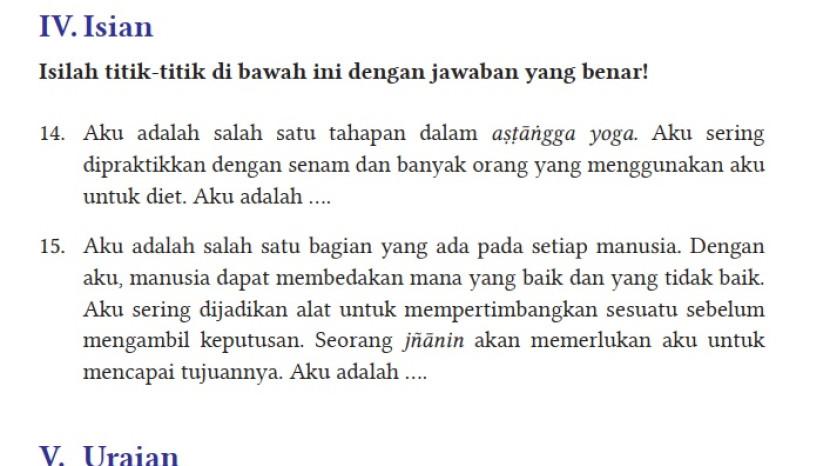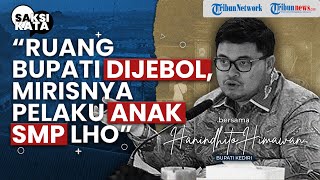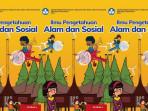Citizen Journalism
Mengembalikan Peran dan Fungsi Awal Ormas
Kebijakan ini beresensi pada pembatasan hadirnya berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), jikapun ada, organisasi-organisasi sosial itu sengaja
Oleh: Wahyu Budi Nugroho (Sosiolog Universitas Udayana)
Dahulu di era Orde Baru, terdapat kebijakan floating mass atau “kebijakan massa mengambang”.
Kebijakan ini beresensi pada pembatasan hadirnya berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), jikapun ada, organisasi-organisasi sosial itu sengaja (telah) dibentuk oleh pemerintah agar mudah disetir dan dikontrol.
Dengan demikian, Ormas semacam ini, bukanlah organisasi sosial yang tumbuh secara alami melalui kekuatan masyarakat, melainkan organisasi sosial yang telah terkooptasi pemerintah, dan sekadar menjalankan agenda-agenda pemerintah.
Hal di atas sudah tentu mendistorsi peran dan fungsi ideal Ormas.
• Makanan dan Minuman Ini Dapat Membantu Anda Mengatasi Rasa Lelah
• Sering Dihindari, Ternyata Minum Air Dingin juga Miliki Manfaat, Termasuk Atasi Heat Stroke
• 4 Pernyataan Ashanty Soal Perselisihan Krisdayanti Dengan Aurel-Azriel Hermansyah
Idealnya, ormas terbentuk dikarenakan kesamaan kepentingan, aspirasi, kehendak, atau kebutuhan yang sama di antara sesama anggota masyarakat.
Aktivitas anggota masyarakat dalam wadah ormas inilah yang kemudian memunculkan istilah “publik”, yakni kumpulan anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap suatu isu atau persoalan yang sama.
Itulah mengapa, terdapat beragam ormas dengan agenda advokasi yang berbeda-beda. Ini pulalah yang menyebabkan istilah ormas tidak tepat jika diartikan sebagai “organisasi massa”, karena secara sosiologis, massa adalah kerumunan yang bersifat sementara, cenderung spontan, dan mudah “terhasut”.
Dengan kata lain, massa adalah kumpulan individu yang kurang memiliki kesadaran kritis, sementara publik dalam ormas adalah kumpulan individu atau kumpulan anggota masyarakat yang sadar akan isu sosial tertentu, kritis, serta berkegiatan secara berkesinambungan.
Sebagai wadah aspirasi masyarakat, ormas memiliki peran penting dalam penciptaan kultur demokrasi.
Semakin banyak ditemui ormas dalam suatu masyarakat, maka semakin baik pula kehidupan demokrasi suatu negara.
Ormas yang dimaksud tentunya adalah organisasi-organisasi sosial yang lahir melalui kekuatan murni masyarakat.
Pentingnya keberadaan ormas bagi kehidupan demokrasi suatu negara setidaknya dengan menilik tiga fungsi utama ormas.
Pertama, sebagai pengartikulasi aspirasi masyarakat.
Seringkali, anggota masyarakat atau warga negara tidak mampu menarasikan atau mengomunikasikan dengan baik persoalan yang dihadapinya.
• Noda Membandel? Coba Cuci Pakaian dengan Sabun Cuci Piring dan Lihat Hasilnya
• Ramalan Zodiak 28 Juni 2020, Langit Sedang Tersenyum Pada Aries, Leo Singkirkan Sikap Angkuhmu
Begitu juga, kerapkali mereka tidak mengetahui sarana-sarana yang harus digunakan untuk mengakses kekuasaan—dalam rangka mengadukan persoalannya.
Serangkaian hal ini umumnya terjadi karena minimnya tingkat kompetensi, pendidikan, serta kurangnya pengalaman dalam advokasi isu-isu sosial.
Oleh karenanya, ormas seyogiyanya hadir sebagai “penyambung lidah masyarakat”. Secara tidak langsung, ini turut menunjukkan fungsi ormas dalam memengaruhi kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kedua, sebagai pengawas pemerintah atau pengontrol kekuasaan. Terdapat tiga elemen sosial utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu lembaga politik (negara, pemerintah, termasuk partai politik), lembaga ekonomi atau swasta, serta masyarakat sipil.
Layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, ormas memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, ormas haruslah berdiri di luar kekuasaan pemerintah.
Ketika ormas berada di dalam lingkaran pemerintah, bahkan berkoalisi dengannya, maka ormas tidak akan bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
Dengan kata lain, ormas hanya akan kembali menjadi kepanjangan tangan pemerintah sehingga mengamputasi fungsi-fungsi sosial murninya.
Ketiga, penciptaan ruang publik.
Berkelindan dengan fungsi pertama, ormas seharusnya tidak hanya bisa membantu menyuarakan masyarakat yang terpinggirkan, tetapi juga membuat mereka mampu bersuara sendiri.
Ormas sarat mendorong kompetensi dan kemampuan nalar publik sehingga diskusi ataupun perdebatan antar sesama warga negara, serta antara warga negara dengan lembaga politik maupun ekonomi dapat terhelat secara bebas dan mandiri—yang pada akhirnya tanpa perantara ormas.
Dalam kondisi setiap warga negara dapat “berdebat secara bebas” itulah ruang publik bakal tercipta, karena setiap anggota masyarakat dapat menjadi subjek pengawas terhadap lembaga politik maupun ekonomi.
Ini menjadi penting dalam kehidupan demokrasi agar warga negara tidak sekadar menjadi penonton pertunjukan politik maupun sirkus ekonomi, melainkan dapat pula merespons dan memengaruhinya.
Dengan demikian, dalam upaya menciptakan masyarakat sipil yang ideal, ormas pun sarat mengembangkan paradigma interaksi-komunikatif dengan masyarakat.
Paradigma ini mengandaikan ketiadaan subyek dan obyek, serta pihak dominan dan yang didominasi dalam interaksi.
Sebaliknya, paradigma kerja dalam interaksi hanya akan menempatkan masyarakat sebagai objek, cenderung didominasi, dan pada akhirnya menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap ormas.
Oleh karenanya, turut menjadi catatan penting kiranya, para pegiat (baca: aktivis) ormas seyogiyanya adalah mereka yang telah menjadi subjek demokrasi, subjek toleransi, dan terutama: subjek kemanusiaan.(*)