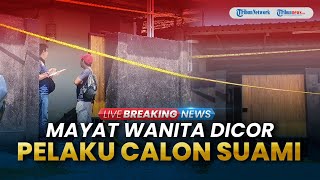Citizen Journalism
Ada yang Tak Kalah Berbahaya dari Rasisme, Yaitu Tubuh Sosial
Namun, banyak pihak tak menyadari jika sesungguhnya fenomena “tubuh sosial” tak kalah berbahaya dibanding rasisme.
Oleh: Wahyu Budi Nugroho (Sosiolog Universitas Udayana)
Beberapa hari terakhir ini kewaspadaan kita akan Covid-19 seolah diinterupsi oleh meninggalnya George Floyd akibat kekerasan polisi di Minneapolis.
Tak pelak, peristiwa itu seakan memunculkan kembali pertanyaan ihwal problem rasisme di Amerika Serikat meski telah disahkannya UU Hak Sipil oleh Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1964.
Namun, banyak pihak tak menyadari jika sesungguhnya fenomena “tubuh sosial” tak kalah berbahaya dibanding rasisme.
Selama ini, fenomena tersebut—tubuh sosial—seolah telah diterima secara “apa adanya”, dan tanpa banyak pihak yang mempertanyakannya.
• Relawan BalaTama Gianyar Salurkan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 secara ‘Door to Door’
• Menteri Agama Keluarkan Surat Edaran Panduan Ibadat di Rumah Ibadah, Ini 11 Kewajiban yang Diatur
• Sambangi Puri Agung Klungkung, AA Gde Agung Serahkan Tali Kasih ke Masyarakat
Tubuh sosial menjadi tak kalah berbahaya daripada rasisme karena memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang rasisme.
Apabila secara sederhana rasisme diartikan sebagai pemahaman atau praktik yang berupaya mendiskriminasi ras atau suku bangsa tertentu; maka tubuh sosial melampaui itu.
Tubuh sosial tak hanya menyoal ciri fisik yang berbeda secara ras, tetapi juga stigma terhadap tubuh yang tak ideal meskipun pada sesama ras, terlebih untuk ras yang berlainan.
Dengan demikian, rasisme tergolong dalam tubuh sosial, akan tetapi tubuh sosial sendiri lebih luas daripada rasisme.
Secara ringkas, kita bisa menyebut tubuh sosial sebagai harapan-harapan ideal akan tubuh kita dan orang lain, dan ketika harapan itu tak terpenuhi, timbullah rasa bersalah dan frustasi pada diri, cemoohan dari orang lain, perundungan, hingga diskriminasi.
Secara konkret, kita bisa memisalkan tubuh sosial lewat tampan/cantik atau ideal-tidaknya tubuh seseorang, juga menarik-tidaknya tampilan seseorang. Hal-hal sepele semacam ini, nyatanya memunculkan implikasi sosial yang tak sepele.
Dewasa ini, budaya pop-lah yang menjadi biang utama akan konstruksi tubuh sosial. Budaya pop, baik itu berupa film, musik, iklan-iklan, sastra, atau yang lainnya; selalu menampilkan mereka yang memiliki keparasan tampang dan tubuh ideal sebagai lakon utamanya.
Hal ini lambat-laun memunculkan definisi akan cantik, tampan, atau menarik yang seakan sarat sedemikian rupa.
Industri kosmetik pun mengambil peluang ini, kemudian berbagai perhelatan untuk merayakan ketubuhan yang indah juga digelar secara berkala guna meneguhkan kesan-kesan itu.
Alhasil, tak sedikit dari mereka, baik orang biasa maupun selebritis yang frustasi bahkan hingga mengakhiri hidupnya karena menuai perundungan penggemarnya, yakni ketika kecantikan atau ketampanan, berikut tubuh mereka tak lagi memenuhi harapan para penggemarnya.
Tak sedikit pula rumah tangga yang hancur akibat tampilan pasangan yang dianggap tak lagi sesuai dengan standar tubuh sosial.
• 5 Manfaat Luar Biasa Air Mawar Untuk Kecantikan, Yuk Buat Sendiri di Rumah!
• Tetap Kece Meski di Rumah Aja, Begini Tips Merapikan Alis Sesuai Bentuk Wajah
• Pelatih Bali United Teco: Liga 1 Indonesia Bisa Contoh Protokol Kesehatan yang DIterapkan Bundesliga
Pun, sudah tak terhitung juga banyaknya pecinta yang patah hati karena ditolak cintanya, akibat tak mampu memenuhi harapan tubuh sosial orang yang dicintainya.
Hal-hal semacam ini menjadi fenomena gunung es tersendiri, dan seringkali kita gagal melihatnya sebagai latar lahirnya serangkaian tragedi sosial yang muncul di permukaan; perundungan, kekerasan, hingga hilangnya nyawa.
Lebih jauh, tubuh sosial pun turut menjadi biang ketidakadilan secara luas, dan ini terjadi secara terang-terangan.
Misalnya, bagaimana hampir di setiap lowongan pekerjaan saat ini selalu menyertakan syarat “berpenampilan menarik” bagi para pelamarnya.
Malah, terdapat penelitian yang menyebutkan jika kini penampilan yang menarik lebih penting daripada kompetensi di dunia kerja.
Tentu, hal-hal semacam ini dapat menimbulkan frustasi bagi mereka yang merasa tak berpenampilan menarik atau merasa tak memiliki keparasan tampang.
Padahal, berbagai kualitas tersebut umumnya bersifat bawaan atau alamiah, dan sulit diubah pada batas-batas tertentu.
Di abad ke-21 ini, rasisme ibarat virus SARS, meskipun praktik-praktiknya tak lagi sebanyak di abad sebelumnya, namun tingkat fatalistiknya tinggi.
Sementara, tubuh sosial ibarat Covid-19, didera oleh jauh lebih banyak orang, namun dengan implikasi fatal yang lebih rendah.
Akan tetapi, kita juga tak bisa menyepelekannya, karena karakter yang disebutkan belakangan kerapkali diam-diam menimbulkan dampak sampingan tak kasat mata yang tak kalah berbahaya.
Sejak dahulu hingga kini, praktik-praktik yang didasarkan pada tubuh sosial dalam kehidupan sehari-hari lebih intens dan masif terjadi melampaui yang kita bayangkan, bahkan pada hal-hal yang tak kita duga sebelumnya.
Bagaimana seorang guru lebih memperhatikan siswa-siswinya yang cantik atau tampan di kelas, bagaimana seorang dosen cenderung memberikan nilai bagus pada mahasiswa atau mahasiswi dengan keparasan tampang dan keidealan tubuh, juga bagaimana kita cenderung menerima dan berprasangka baik terhadap mereka yang cantik atau tampan dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Inilah mengapa tubuh sosial sebetulnya tak kalah berbahaya, ia memberikan berbagai penilaian picik melampaui ciri fisik suatu ras atau suku bangsa.(*)